Saya percaya bahwa teknologi membawa banyak potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan adopsi digital sifatnya adalah wajib. Namun, ketika saya mulai masuk ke ranah ilmu sosial, saya cukup terkejut. Ternyata, ada banyak kritik terhadap teknologi yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Bagaimana jika digitalisasi justru menghilangkan pekerjaan? Bagaimana jika teknologi membuat interaksi kita kehilangan empati? Bahkan, bagaimana jika sistem yang kita bangun malah memperkuat ketimpangan? Kritik-kritik ini terasa asing, bahkan agak mengganggu. Saya ceritakan sedikit pengalaman masa lalu dan menghubungkan refleksi pribadi dengan gagasan beberapa ilmuwan komputer—yang, sebenarnya, juga punya niat baik dalam membayangkan arah transformasi digital.
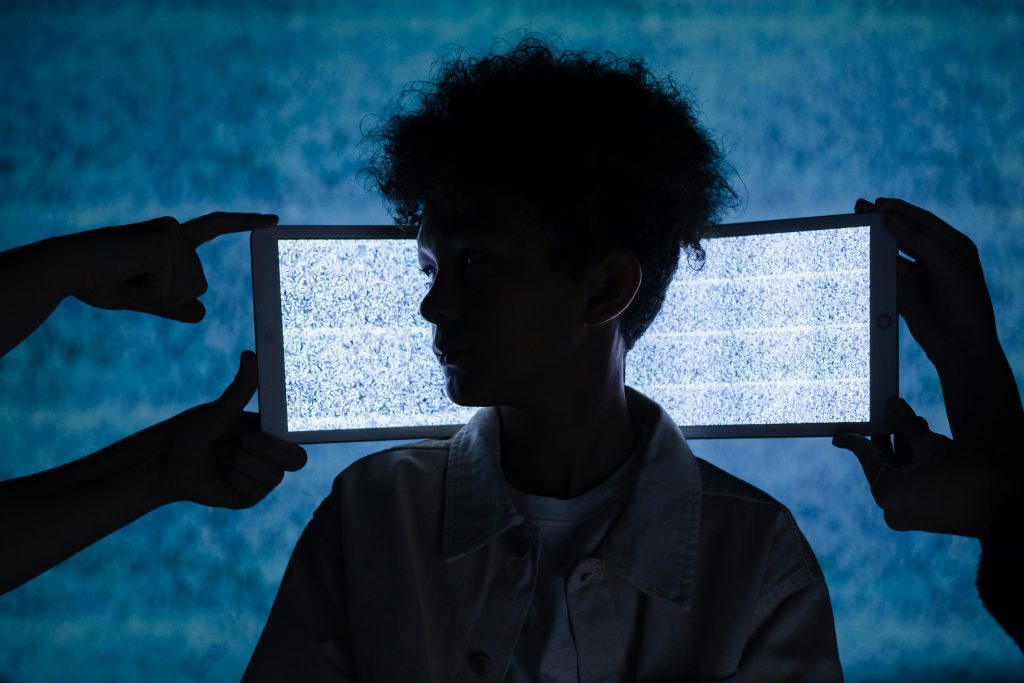
Semangat Beradu Ide untuk Kontribusi Sosial
Pada tahun 2012, saya mengikuti kegiatan pitching ide startup di Stanford University dan bertemu langsung dengan para tech entrepreneurs di Silicon Valley. Saat itu, atmosfer inovasi digital—termasuk dalam hackathon dan berbagai kompetisi ide—dipenuhi semangat untuk menciptakan dampak sosial, sekaligus peluang bisnis. Kami berlomba-lomba merancang solusi untuk apa yang kami anggap sebagai “masalah sosial paling mendesak”, sambil membayangkan bagaimana solusi itu bisa tumbuh menjadi model bisnis yang berkelanjutan dan layak didanai.
Saya dan tim saat itu mengusulkan sistem berbasis ponsel fitur yang memungkinkan pengguna menerima pesan promosi dan newsletter dari perusahaan dengan imbalan poin. Poin tersebut dapat ditukar dengan kuota data atau pulsa. Konsep dasarnya sederhana: informasi adalah mata uang, dan jika dikelola dengan tepat, ia bisa menjadi jembatan antara pelaku usaha dan masyarakat.
Para juri yang merupakan investor melihatnya sebagai upaya untuk “closing the loop” antara perusahaan dan konsumen—dan ide kami pun terpilih sebagai pemenang. Tentu saat itu saya tidak membayangkan bahwa dunia digital akan berkembang menjadi ruang yang penuh notifikasi dan persaingan perhatian seperti sekarang. Yang saya tahu, saat itu, adalah bahwa saya ingin teknologi digunakan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Realitas di Sektor Publik
Tahun 2022, saya mulai masuk ke dunia transformasi digital di sektor publik. Jika kita melihat layanan digital yang kita terima dari pemerintah hari ini, mudah sekali disimpulkan bahwa kita masih sangat membutuhkan transformasi digital. Citra digitalisasi pemerintah masih buruk: sistem-sistem tidak saling terhubung, antarmuka sering kali membingungkan, dan banyak proses masih berjalan setengah manual. Bahkan, ada anggapan bahwa sistem digital sengaja dibuat tidak optimal agar pekerjaan tidak tergantikan, atau agar praktik-praktik korupsi tidak terlalu terekspos.
Dari sudut pandang saya sebagai orang teknik, tentu saja keinginan awal saya adalah terus mendorong agar sistem digital bekerja dengan baik. Tapi kemudian saya juga memahami mengapa banyak mahasiswa atau lulusan teknologi informasi enggan bekerja di sektor publik. Mereka merasa ruang untuk berinovasi begitu terbatas—tidak ada fleksibilitas untuk “mengutak-atik” sistem, bereksperimen, atau mencari solusi out of the box seperti yang biasa dilakukan dalam budaya startup. Budaya birokrasi dianggap terlalu kaku untuk kreativitas teknologi yang ingin banyak mencoba dan belajar dari kegagalan.
Namun, setelah beberapa kali terlibat dalam proyek digitalisasi, saya menyadari bahwa banyak inisiatif transformasi digital dijalankan seperti proyek lepas, tanpa ruang diskusi yang memadai tentang prinsip-prinsip kepublikan. Tahun 2020, saya terlibat dalam salah satu proyek pemerintah yang menjadi bagian dari agenda Making Indonesia 4.0. Visi besar program ini memang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan UMKM, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur digital.
Sayangnya, dalam praktiknya, fokus lebih banyak diarahkan pada target teknis dan efisiensi belaka. Kritik banyak bermunculan bahwa inisiatif ini mengabaikan nilai-nilai seperti partisipasi publik dan keadilan sosial. Hal ini saya alami langsung, ketika keputusan-keputusan utama hanya diambil oleh pemegang tender dan perwakilan pemerintah, sementara pihak-pihak yang terdampak langsung hanya dilibatkan sebagai sumber data.
Dari pengalaman tersebut, saya semakin merasakan adanya disconnect antara wacana besar transformasi digital dan realitas pengembangannya di lapangan—terutama dalam proyek-proyek pengembangan perangkat lunak di sektor publik. Nilai-nilai publik jarang dibicarakan. Diskusi sering kali hanya berputar pada satu hal: bagaimana sistem ini bisa segera “live”. Mungkin sudah saatnya kita menyisipkan kembali nilai-nilai publik ke dalam proses pengembangan sistem informasi, bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai fondasi.
Bagaimana Pemikiran Ilmuwan Teknologi?
Jika kita menelusuri pemikiran para ilmuwan di bidang ilmu komputer, sebenarnya gagasan ini bukan hal baru. Douglas Engelbart, misalnya, sejak awal telah memandang teknologi bukan sebagai pengganti manusia, tetapi sebagai alat untuk augmenting human intellect. Saat kuliah master, saya berkali-kali menonton dokumentasi saat Engelbart pertama kali memperkenalkan mouse dan word processor, yang di dalamnya terdapat konsep real-time collaborative editing, yang jauh mendahului zamannya.
Bagi Engelbart, teknologi adalah perpanjangan dari kecerdasan kolektif manusia. Maka jika sistem digital justru membuat masyarakat merasa kecil atau tidak berdaya, barangkali kita telah melenceng dari arah yang ia bayangkan.
Bagi Engelbart, teknologi adalah perpanjangan dari kecerdasan kolektif manusia. Maka jika sistem digital justru membuat masyarakat merasa kecil atau tidak berdaya, barangkali kita telah melenceng dari arah yang ia bayangkan.
Pemikiran lain datang dari Paul Dourish, yang memperkenalkan konsep embodied interaction—bahwa interaksi manusia dengan sistem digital tidak bisa dilepaskan dari tubuh, ruang fisik, dan konteks sosial. Dalam dunia HCI, konsep ini digunakan untuk merancang sistem yang imersif dan lebih manusiawi. Menurut saya, pendekatan ini sangat relevan untuk merancang layanan publik dalam sistem sosial-teknikal (sociotechnical systems). Teknologi tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu dibentuk oleh dan ikut membentuk praktik sosial di sekitarnya.
Lalu ada Lucy Suchman, dengan gagasan situated action, yang menolak anggapan bahwa interaksi manusia bisa direpresentasikan secara sepenuhnya logis dan terstruktur. Manusia berinteraksi dalam konteks yang cair dan dinamis—dan sistem digital perlu memahami itu. Dalam konteks saat ini, ketika kecerdasan buatan (AI) semakin banyak digunakan, saya justru melihat potensi: AI dapat menjadi enabler bagi sistem yang lebih kontekstual, selama kita arahkan untuk memahami, bukan menggantikan.
Pendekatan context-aware computing, yang sudah lama menjadi bidang kajian tersendiri, mendukung pandangan Suchman bahwa sistem harus mampu membaca situasi, bukan hanya menjalankan logika.
Dari pemikiran-pemikiran tersebut, semakin jelas bagi saya bahwa transformasi digital seharusnya tidak netral. Ia membawa nilai, dan harus dikembangkan dengan kesadaran akan nilai itu. Bukan sekadar membuat sesuatu yang “digital”, melainkan sesuatu yang bermakna.
Menjembatani Dua Dunia
Idealisme ini sebenarnya tidak hanya hidup dalam dunia teori. Dalam praktik tata kelola sistem informasi, kerangka seperti ITIL dan TOGAF pun sudah memasukkan nilai sebagai prinsip dasar. ITIL 4, misalnya, mengusung prinsip “focus on value”, yang mengajak kita bertanya sejak awal: siapa pemangku kepentingannya? Apa yang mereka anggap bernilai? TOGAF juga menekankan pentingnya keselarasan antara visi digital dan hasil yang dicapai.
Sayangnya, prinsip-prinsip ini sering kali hanya berhenti di dokumen. Jika tidak benar-benar dihayati dan dijadikan bagian dari proses, nilai-nilainya tidak akan hidup. Kita terlalu terbiasa menjadikan transformasi digital sebagai proyek teknis, bukan proses sosial.
Padahal, di banyak negara, nilai-nilai publik untuk transformasi digital sudah mulai dirumuskan sebagai pedoman. Jika sudah menjadi aturan main di tingkat negara, seharusnya bisa diadopsi pula dalam praktik sehari-hari.
Melalui tulisan ini yang ingin saya sampaikan adalah: ada jarak yang belum terjembatani antara dua dunia yang saling tidak saling menyapa. Para pemikir teknologi sudah lama menyuarakan pentingnya nilai sosial. Kerangka praktik pun sebenarnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita menyepakati bahwa nilai-nilai tersebut menjadi prinsip bersama agar setiap transformasi digital juga manusiawi dan bermakna.

Leave a Reply